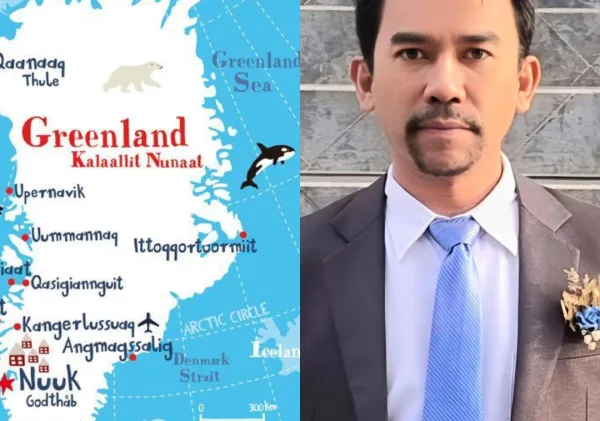Serang — Sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan juga budaya, industri, dan identitas yang diakui di kawasan Eropa. Di balik keberhasilan sepak bola benua biru, terdapat sistem yang kuat dan mendasar yang menghasilkan keunggulan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi refleksi atas kegagalan Tim Nasional Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Terdapat kesamaan antara perkembangan sistem sepak bola Eropa dengan evolusi teori organisasi dan manajemen di dunia Barat. Setidaknya, terdapat tiga fondasi utama yang menopang kemajuan sepak bola Eropa, yang dapat diibaratkan sebagai tahapan perkembangan teori manajemen modern.
1. Pembinaan Holistik dan Terstruktur
Di Eropa, setiap klub memiliki filosofi bermain yang ditanamkan sejak usia dini, seperti Total Football di Belanda atau sistem La Masia di Spanyol. Pembinaan menekankan pada teknik, visi bermain, pengambilan keputusan, dan kemampuan taktis yang dikembangkan secara teratur dan berkesinambungan.
Pendekatan ini mencerminkan Teori Klasik dalam manajemen, seperti Taylorisme dan Administrasi Fayol, yang menekankan efisiensi, struktur kerja, dan koordinasi yang sistematis. Pembinaan sejak dini berfungsi sebagai bentuk spesialisasi dan koordinasi dalam organisasi yang disiplin.
2. Industri Profesional dan Sistem Birokrasi
Sepak bola Eropa beroperasi layaknya industri yang sangat profesional. Setiap elemen, mulai dari liga, klub, hingga aspek pemasaran, dikelola dengan standar internasional. Kompetisi yang ketat menuntut transparansi, efisiensi, dan profesionalitas tinggi.
Struktur tersebut mencerminkan konsep birokrasi Max Weber, yang menekankan pentingnya hierarki, aturan formal, serta kesetaraan dalam pelayanan. Dengan sistem manajemen yang matang dan stabil, sepak bola Eropa berhasil membangun ekosistem yang terorganisir dan berkelanjutan.